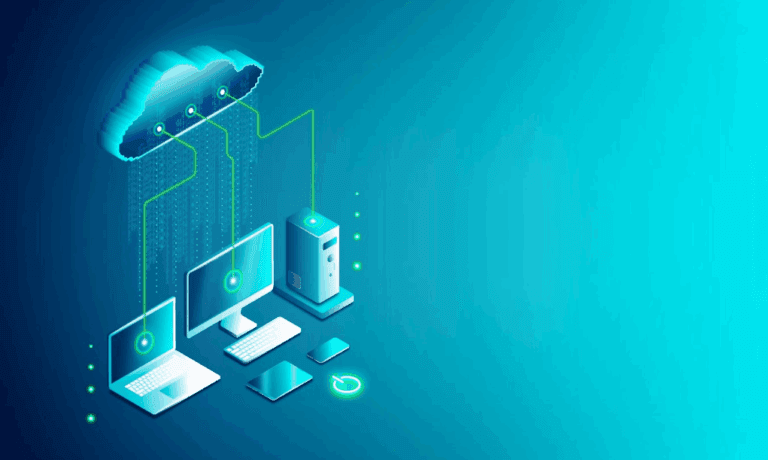Diam. Sesal. Berat. Tiga kata yang mewakili perasaanku saat aku mengetahui dengan nyata bahwa di lauhul mahfuz aku ditakdirkan menjadi yatim. Sejak April 2010, aku sudah dihentak dengan kenyataan Ayah sakit. Awalnya kusangka hanya penyakit biasa saja tanpa harus dikhawatirkan lebih dalam.
Berhari-hari sepertinya semakin tidak bisa terprediksi. Kondisi Ayah memburuk. Semakin kurus bahkan sempat hanya seperti tulang dibaluti kulit. Kurus kering. Aku sedih melihat Ayah seperti itu. Dilema karena di satu sisi harus menyenangkan Ayah agar studi selesai. Hingga menjelang Oktober 2010, batinku terkoyak. Mimpi buruk menjadi nyata. Ayah pergi untuk selamanya. Aku terdiam meskipun terus bergerak mengurusi kelengkapan pemakaman Ayah. Sedikit demi sedikit orang yang melayat Ayahku memeluk dan menangis di pelukanku. Air mataku jatuh tetapi suaraku hilang. Diam.
Setelah Ayah dimakamkan. Aku masih sempat tersenyum karena lega sebab Ayah kini tak menderita lagi. Penyakitnya diangkat Tuhan bersama ruh yang dititipkan kepada Ayah. Entah mengapa sejak hari itu aku tidak peduli lagi dengan studiku. Toh, Ayah sudah pergi dan tidak menepati janji. Ayah berjanji akan datang di hari aku wisuda untuk yang kedua kalinya. Tetapi sekarang Ayah malah hilang dan tidak lagi menyemangati. Aku benci. Itu anggapanku hingga setiap hari yang kulakukan hanya menghabiskan waktu dan tak menghasilkan apa-apa. Terpuruk pada kondisi kesedihan yang larut.
Berpuluh-puluh pesan singkat (baca: SMS) datang dari teman-teman kampus. Mereka menginginkan aku ke kampus dan kembali menyelesaikan tesis yang tinggal menyusun tahap akhir. Penelitian memang sudah kulakukan hingga memperoleh hasil maksimal tetapi laporan penelitiannya masih dalam bentuk file mentah. Belum kusentuh sama sekali. Semua karena batinku belum siap menerima kenyataan kalau Ayah benar-benar tiada.
Suatu malam aku tertidur karena keletihan menangis. Antara nyata dan tidak, aku melihat Ayah datang dengan pakaian putih bersih, harum dengan minyak wangi yang suka Ayah pakai kalau akan melaksanakan sholat Jum’at. Namun, wajah Ayah saat itu murung. Aku mencoba bertanya kenapa wajahnya murung, tetapi Ayah tidak menjawab satu kata pun. Keesokan harinya juga demikian hingga hari ketiga.
Karena mimpi itu aku tersadar. Ayah tidak ingin aku seperti saat itu. Diam dan tidak bersemangat dalam hidup. Bahkan kuliah yang menjadi harapan Ayah kuabaikan karena hilangnya semangat. Akhirnya aku memantapkan hati agar mencoba kuat dengan kondisi saat ini. Aku mulai membuka diri dan bergaul kembali dengan teman-teman. Meskipun terkadang aku miris melihat teman-teman yang masih memiliki orang tua lengkap.
Ternyata perjalanan menempuh masa wisuda dipermudah Tuhan. Aku yakin ini karena Ayah juga. Doa-doa Ayah untukku akhirnya bisa kurasakan sekarang. aku bisa selesai dengan waktu yang tidak melewati masa studi. Dan yang lebih membuatku takjub karena prosesi ujian sidangku tak lebih dari satu jam bahkan kurang.
Ibarat sebuah sinteron, setelah aku ujian sidang, aku bermimpi kembali Ayah datang dengan senyum khasnya. Memelukku meskipun tetap tanpa kata-kata. Aku tahu Ayah ingin aku tetap bersemangat untuk melanjutkan hidupku. Sebab setiap manusia memiliki jalan takdirNya masing-masing. Ayah memang saat ini sudah tiada tetapi aku yakin di sana senyumnya terus merekah karena aku bisa bangkit dari kesedihan.

*Cerita ini diikutkan dalam CHIC Blog Competition 2013